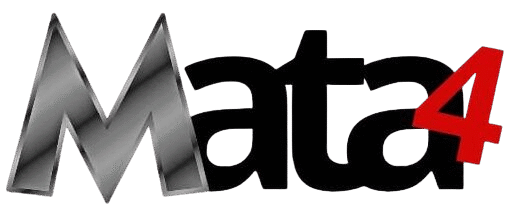Papua, Mata4.com — Upaya konservasi mangrove dan lahan gambut di Indonesia kini menghadapi tantangan yang tidak hanya bersifat teknis dan ekologis, tetapi juga sosial dan struktural. Di balik program-program nasional maupun internasional yang terus digencarkan, masih terdapat kesenjangan besar antara pendekatan kebijakan konservasi dan realitas di tingkat komunitas lokal.
Mangrove dan lahan gambut merupakan ekosistem yang sangat penting — tidak hanya bagi mitigasi perubahan iklim, tetapi juga untuk ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat pesisir serta pedalaman. Namun, selama ini konservasi sering kali dilakukan dari atas ke bawah (top-down), tanpa melibatkan secara bermakna masyarakat yang hidup dan bergantung pada ekosistem tersebut.
Kini, muncul kesadaran bahwa solusi jangka panjang hanya bisa dicapai jika konservasi benar-benar berakar dalam komunitas lokal.
Mangrove dan Lahan Gambut: Garda Depan Krisis Iklim
Indonesia memiliki salah satu cadangan karbon terbesar di dunia yang tersimpan dalam ekosistem mangrove dan gambut. Ekosistem ini berfungsi sebagai penyerap karbon (carbon sink), pelindung pantai dari abrasi, pengendali banjir, serta rumah bagi keanekaragaman hayati.
Namun kenyataannya, degradasi lahan gambut dan alih fungsi hutan mangrove terus terjadi. Penyebabnya beragam: dari pembukaan lahan untuk industri, pertanian intensif, hingga pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, tekanan terhadap masyarakat lokal yang hidup dari sumber daya alam juga membuat konservasi semakin kompleks.
Kesenjangan dalam Praktik Konservasi
Berbagai program konservasi sering kali dirancang tanpa partisipasi aktif masyarakat lokal. Banyak inisiatif yang membawa teknologi canggih, pendekatan saintifik, dan skema pendanaan global, namun gagal menjawab kebutuhan serta kearifan lokal yang telah ada selama puluhan tahun.
Contohnya, proyek rehabilitasi mangrove yang menanam pohon tanpa mempertimbangkan jenis lokal dan siklus pasang-surut laut justru berakhir gagal. Begitu juga program restorasi gambut yang mengabaikan praktik tradisional masyarakat, seperti sistem kanal air lokal yang selama ini digunakan untuk bertahan hidup.

www.service-ac.id
Berakar dalam Komunitas: Pendekatan yang Inklusif
Kini mulai tumbuh pendekatan baru yang disebut sebagai konservasi berbasis komunitas (community-based conservation). Di banyak wilayah, seperti di pesisir Kalimantan, Sumatera, dan Papua, sejumlah organisasi masyarakat sipil, LSM lingkungan, dan pemerintah daerah mulai menempatkan masyarakat sebagai aktor utama konservasi, bukan sekadar penerima program.
Beberapa prinsip pendekatan ini antara lain:
- Partisipasi aktif warga lokal dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program konservasi.
- Pengakuan terhadap kearifan lokal dan hak atas wilayah kelola, termasuk praktik-praktik tradisional yang terbukti berkelanjutan.
- Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui model ekowisata, pertanian organik, atau perikanan ramah lingkungan berbasis mangrove.
- Transparansi dan dialog antara pemerintah, peneliti, dan komunitas, sehingga konservasi tidak menjadi agenda sepihak.
Studi Kasus: Harapan dari Akar Rumput
Di Desa Tanjung Batu, Kalimantan Timur, komunitas nelayan bekerja sama dengan LSM lokal membentuk kelompok masyarakat peduli mangrove. Mereka tidak hanya menanam mangrove secara rutin, tapi juga mengembangkan produk turunan seperti sirup buah mangrove dan ekowisata perahu kanal.
Sementara itu, di wilayah gambut di Sumatera Selatan, kelompok tani mempraktikkan pertanian tanpa bakar dengan dukungan pelatihan dan insentif dari pemerintah daerah. Pendekatan ini terbukti menekan kebakaran hutan dan memperkuat ekonomi petani.
Tantangan dan Masa Depan
Meski pendekatan berbasis komunitas menjanjikan, tantangan tetap ada. Masih banyak kebijakan nasional yang belum sejalan dengan kondisi lapangan. Persoalan legalitas hak atas lahan, keterbatasan akses pendidikan lingkungan, dan minimnya insentif ekonomi membuat sebagian masyarakat kembali pada praktik-praktik merusak.
Namun dengan dukungan yang tepat, masyarakat lokal dapat menjadi mitra strategis dalam melindungi lingkungan. Sebab, mereka bukan hanya penjaga hutan dan pesisir, tetapi juga pewaris dan pelindung masa depan ekologis bangsa.
Kesimpulan: Waktunya Mengakar, Bukan Sekadar Menanam
Konservasi tidak bisa hanya dilakukan dengan pendekatan teknokratis dan sesekali kunjungan proyek. Ia harus tumbuh dari bawah, mengakar dalam komunitas, mendengarkan mereka, melibatkan mereka, dan menghormati kearifan lokal.
Jika Indonesia ingin menjaga mangrove dan lahan gambut untuk generasi mendatang, maka inilah saatnya membangun jembatan — bukan hanya antara darat dan laut, tapi antara kebijakan dan kenyataan, antara ilmuwan dan nelayan, antara peta satelit dan kaki-kaki yang sehari-hari melintasi lumpur.
Karena masa depan lingkungan hidup Indonesia, pada akhirnya, terletak di tangan mereka yang hidup paling dekat dengan alam itu sendiri.