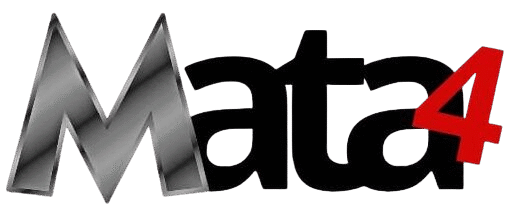Jakarta, Mata4.com — Isu tentang kembalinya pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara tidak langsung kembali mencuat di tengah dinamika politik nasional. Wacana ini menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan, terutama setelah beberapa politisi dan pengamat menyatakan bahwa sistem Pilkada langsung selama ini cenderung memicu politik berbiaya tinggi, yang kerap berujung pada praktik korupsi, politik uang, dan keterlibatan oligarki.
Namun di sisi lain, banyak pihak juga menilai bahwa Pilkada langsung merupakan instrumen penting dalam memperkuat demokrasi partisipatif, di mana rakyat diberi hak secara langsung untuk memilih pemimpin daerahnya tanpa perantara elit politik.
Lantas, benarkah Pilkada tak langsung bisa menjadi solusi atas mahalnya ongkos politik? Atau justru menjadi langkah mundur dalam perjalanan demokrasi Indonesia?
Latar Belakang: Mahalnya Ongkos Politik dalam Pilkada Langsung
Sejak diberlakukan pada 2005, Pilkada langsung dinilai membawa semangat reformasi dan desentralisasi yang menguatkan posisi rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Namun, dalam praktiknya, sistem ini kerap dikritik karena mendorong kompetisi yang mahal dan transaksional, baik bagi kandidat maupun partai pengusung.
Berbagai studi dan laporan Lembaga Swadaya Masyarakat menunjukkan bahwa biaya yang harus dikeluarkan calon kepala daerah sangat tinggi, mulai dari biaya kampanye, logistik, hingga biaya “pengamanan suara” yang sering kali bersifat ilegal.
Sebagai contoh, beberapa laporan menyebutkan bahwa untuk memenangkan satu kursi bupati atau wali kota, seorang kandidat bisa menghabiskan antara Rp10 hingga Rp50 miliar, tergantung pada wilayah dan tingkat kompetisi. Sumber pendanaan yang tidak transparan inilah yang kemudian membuka celah korupsi saat kandidat terpilih menjabat.
Wacana Pilkada Tak Langsung: Solusi atau Ilusi?
Wacana mengembalikan Pilkada ke sistem tak langsung — di mana kepala daerah dipilih oleh DPRD — diangkat kembali oleh sejumlah elit politik dan tokoh pemerintahan. Alasan utama yang dikemukakan adalah efisiensi anggaran dan reduksi politik uang.
Namun, kritik tajam datang dari banyak pihak. Mereka menilai sistem Pilkada tak langsung justru berpotensi memperkuat oligarki lokal dan mempersempit ruang partisipasi publik. Jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka kemungkinan besar prosesnya akan berlangsung secara tertutup, elitis, dan rawan negosiasi politik transaksional di tingkat legislatif daerah.
“Jika kita kembali ke Pilkada tak langsung, maka demokrasi hanya akan dinikmati oleh segelintir orang, dan rakyat kehilangan kendali terhadap kepemimpinan di daerah mereka,” ujar seorang pengamat politik dari LIPI.

www.service-ac.id
Risiko Politik Dinasti dan Oligarki Lokal
Salah satu kekhawatiran dari sistem Pilkada tak langsung adalah potensi suburnya politik dinasti dan dominasi oligarki lokal. Dalam sistem ini, partai-partai politik memiliki kontrol penuh atas siapa yang terpilih, dan rakyat hanya menjadi penonton.
Padahal dalam sistem Pilkada langsung, meskipun tidak sempurna, masyarakat masih memiliki peran dan harapan untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan aspirasi mereka. Banyak tokoh daerah yang bukan berasal dari elite politik bisa naik ke panggung karena dipilih langsung oleh rakyat.
Dengan Pilkada tak langsung, potensi munculnya pemimpin alternatif bisa tertutup, dan posisi kepala daerah cenderung diberikan pada mereka yang punya koneksi dan “modal politik” dalam internal partai, bukan karena kualitas atau elektabilitas di mata rakyat.
Apa Solusinya? Reformasi Bukan Mundur
Pilkada langsung memang tidak sempurna. Biaya politik yang tinggi, politik uang, hingga lemahnya literasi politik masyarakat menjadi tantangan besar. Namun, solusi yang bijak bukanlah menghapus hak rakyat untuk memilih, melainkan memperbaiki sistem yang ada.
Beberapa alternatif solusi yang bisa dipertimbangkan antara lain:
- Pembatasan dan transparansi dana kampanye, serta audit independen terhadap sumber pendanaan calon kepala daerah.
- Pendidikan politik massal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilih calon pemimpin yang berkualitas, bukan hanya populer atau bermodal besar.
- Penguatan lembaga pengawas pemilu (Bawaslu dan KPU) agar lebih independen dan efektif dalam menindak pelanggaran politik uang.
- Regulasi ketat terhadap sumbangan kampanye dari pihak ketiga, termasuk perusahaan atau kelompok kepentingan.
Kesimpulan: Demokrasi Bukan Hanya Soal Murah atau Mahal
Biaya tinggi dalam Pilkada bukan alasan yang cukup kuat untuk mencabut hak rakyat dalam memilih pemimpinnya secara langsung. Demokrasi bukan sekadar soal efisiensi, tapi soal partisipasi, keterbukaan, dan kepercayaan rakyat terhadap sistem politik.
Mengembalikan Pilkada ke sistem tak langsung sama saja dengan memundurkan roda demokrasi Indonesia ke era sebelum reformasi. Dalam situasi politik yang makin kompleks dan terkadang penuh intrik, yang dibutuhkan bukan pembatasan partisipasi, tapi penguatan mekanisme demokrasi yang lebih adil, bersih, dan transparan.